Oleh: YRS
Di hari libur yang lenggang, ketika matahari seperti enggan naik terlalu tinggi dan angin berjalan pelan-pelan seolah sedang merenung, Andara melangkah ke Kelng Kumang Forest bersama kawan-kawan lamanya, alumni SMEA Budi Luhur Sintang. Taman Kelempiau menyambut mereka seperti seorang ibu tua yang bijak: tahu kapan harus bicara, tahu kapan hanya diam memandang, tahu bagaimana mengajak seseorang pulang pada dirinya sendiri.
Langkah-langkah mereka menyentuh tanah dengan ringan, seakan takut membangunkan sejarah yang tidur di bawah akar-akar tua. Akar-akar itu menjulur dari tanah seperti tangan-tangan masa lalu, mencoba menyentuh kembali yang pernah hilang, cinta remaja yang tak sempat diucap, tawa-tawa yang tak pernah sempat diabadikan, dan rahasia yang terkubur bersama ijazah sekolah.
Hutan itu punya jembatan. Sederhana, dari kayu tua yang mengeluarkan bunyi retak kecil saat diinjak. Tapi di atasnya tergantung tulisan yang mengusik:
“Jalan sama dia, nikah sama aku.”
Tulisan itu seperti mantera anak kecil yang sedang belajar melawan dunia dengan puisi. Mungkin kutukan, mungkin lelucon, atau bisa jadi hanya doa kesepian yang tersesat dan menggantung di udara.
Para gadis berkerumun di sana. Tertawa, berpose, berteriak pelan kepada ponsel masing-masing, meminta cahaya sore untuk bersikap adil. Dan di antara mereka, Andara berdiri dengan mata setenang danau pagi hari—mata yang tahu caranya menyimpan rahasia tanpa membuatnya membusuk. Ia mengatur rambutnya pelan, seolah tahu ada langit yang sedang jatuh hati padanya.
Lalu muncullah Rino. Lelaki yang datang sendiri, membawa ransel kecil dan dada yang penuh suara-suara tak terdengar. Ia datang bukan mencari cinta, bukan juga melarikan diri. Ia hanya ingin berjalan. Tapi jalannya terhalang oleh sekumpulan perempuan yang sedang mencoba menahan kenangan di balik lensa kamera.
Ia jengkel. Tapi kejengkelan itu hanya seperti asap dari korek api: sebentar, lalu hilang ketika dari celah kerumunan itu, sepasang mata menangkapnya. Mata Andara. Tatapan itu menghentikan waktu seperti rem patah dalam film bisu. Ia lupa bahwa di rumah, ada seorang istri yang sedang menjemur baju dan menyusun harapan.
“Mas, tolong fotoin kami dong,” suara Andara meluncur seperti daun yang jatuh tapi tak pernah menyentuh tanah. Pelan, ringan, tapi menggoyang langit.
Rino mengangguk. Tanpa sadar. Ia potret mereka. Bukan hanya dengan kamera ponsel, tapi dengan hatinya yang mendadak bising. Degup yang sebelumnya teratur kini seperti drum perang yang salah pukul.
Setelah tawa dan lambaian tangan, nama-nama ditukar, dan nomor HP diselipkan seperti rahasia kecil yang tidak minta izin. Seolah tak ada gravitasi dalam etika. Seolah semesta sedang lengah.
Dan malam-malam pun datang. Membawa percakapan ringan yang perlahan menebal. Chat demi chat, seperti angin yang menyentuh leher: lembut, menggoda, tak terlihat tapi membuat bulu kuduk berdiri.
Andara tak tahu Rino sudah beristri. Ia pikir lelaki itu seperti puisi yang lupa judul, tapi terlalu enak untuk dibaca ulang. Kalimat-kalimatnya manis, datar, tapi menyimpan arus yang bisa menyeret siapa pun ke dalamnya.
“Lucu ya, tulisan di jembatan itu,” tulis Andara suatu malam.
“Lucu tapi menyeramkan,” balas Rino.
“Kenapa menyeramkan?”
“Karena aku jalan sama kamu…”
Andara tersenyum. Senyum yang tak dilihat siapa-siapa, tapi terasa di seluruh tubuhnya. Senyum yang membungkus tidur malamnya dengan mimpi-mimpi absurd tentang kemungkinan.
Namun di seberang sana, di sebuah rumah yang tak jauh dari pertengkaran, seorang perempuan menemukan chat-chat itu. Ia duduk diam, matanya menelusuri layar dengan kesabaran yang tak berbelas kasih. Lalu ia berdiri. Dan dunia mulai goyah.
“Siapa Andara?” tanyanya dengan suara yang tidak meninggikan nada, tapi menurunkan segalanya: langit-langit rumah, harga diri, cinta yang pernah dikira abadi.
Rino tergagap. Kata-katanya seperti ikan yang ditarik dari air: hidup, tapi kehilangan udara. Ia mencoba menjelaskan, tapi penjelasan itu justru memperparah luka.
Pertengkaran pun pecah. Meja dibanting. Suara piring pecah terdengar seperti doa yang diludahi. Cinta dituding, kesetiaan dipermalukan. Janji-janji yang dulu dibangun seperti rumah kayu kini menjadi debu yang dipaksa disapu sebelum sempat mengering.
Rino duduk diam setelah itu. Lelah. Bukan pada istrinya, tapi pada dirinya sendiri yang terlalu percaya bahwa hati bisa dibagi rata.
Sementara itu, Andara tak tahu apa-apa. Di sisi lain layar ponselnya, ia menunggu balasan yang tak kunjung datang. Hari-hari terasa lambat, seperti perahu tanpa layar yang tetap bergerak hanya karena arus malas.
Dan ketika kabar akhirnya sampai padanya—bahwa Rino ternyata sudah menikah, bahwa dirinya hanya menjadi musim lewat bagi lelaki yang tak bisa memelihara satu taman saja—ia hanya tersenyum getir. Lalu menghapus pesan-pesan itu satu per satu, seperti menghapus puisi dari dinding kamar: menyisakan bekas, tapi tak lagi terbaca.
“Dasar laki-laki,” batinnya bergema seperti doa yang tak sempat diaminkan,
“tidak cukup satu istri, pinginnya nambah terus… kanyiii…”
Lalu ia ingat jembatan itu. “Jalan sama dia, nikah sama aku.”
Mungkin itu bukan lelucon. Mungkin itu peringatan. Atau sumpah sunyi dari seseorang yang pernah patah lebih dalam dari dirinya.
Dan kini, hutan kembali diam. Akar-akar tua tetap menjulur, angin tetap menyusup di antara batang-batang pohon. Tapi ada sesuatu yang berubah. Di sana, jembatan itu masih tergantung. Goyang pelan oleh angin. Menunggu cerita baru, mungkin tragedi baru. Dan tulisan itu masih di sana—menggoda langit, menggoda hati, menggoda kita yang percaya bahwa cinta bisa disembunyikan di balik percakapan digital.
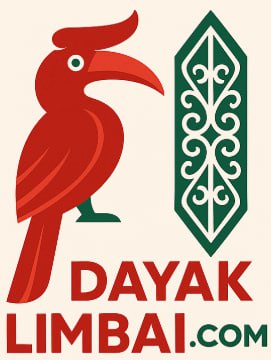











Komentar