Setahun kemudian, pada 1999, lembar baru kehidupan Tingang dibuka perlahan, seperti matahari pagi yang malu-malu menembus kabut. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Setya Budi di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi sebuah kota kecil yang dipeluk oleh gemuruh sunyi Sungai Melawi.
Saat memasuki SMP, cita-cita baginya hanyalah bayangan kabur di kejauhan. Tingang seperti remaja lain yang sedang menari di ujung pelangi masa muda penuh warna, penuh gejolak. Ia cukup cerdas, tapi sering hilang dari kelas seperti daun gugur yang terbawa angin. Akibatnya, setiap kenaikan kelas, ia selalu menempati posisi “tiga dari buntut”. Sebuah julukan yang tak membanggakan, tapi mengandung cerita.
Tingang tidak pernah benar-benar sendiri. Ia memiliki teman dekat yang menjadi lentera di kala gelap, pelipur saat hati tenggelam. Teman itu adalah seorang gadis Tiwi namanya. Cantik seperti embun pagi di pucuk daun, rambutnya panjang, sedikit ikal bergelombang seperti ombak tenang di tepian danau. Tubuhnya semampai, sikapnya lemah lembut, dan tawanya—ah, tawanya—bisa meluruhkan beban di pundak siapa saja yang mendengarnya.
Hari-hari SMP mereka diisi dengan tawa, tugas, dan kenakalan kecil yang tumbuh dari rasa ingin tahu. Sesekali, sepulang sekolah, mereka berjalan menyusuri tepian Sungai Melawi bersama teman-teman lain. Sungai itu menjadi saksi diam, tempat rahasia kecil dititipkan pada angin, tempat kebersamaan mengalir tanpa paksaan.
Suatu sore, langit menggantungkan awan lembut seperti kapas. Mereka berjanji berjalan-jalan sepulang sekolah, dan tentu saja Tiwi adalah yang paling ditunggu kehadirannya. Mereka menyusuri jalan setapak yang belum beraspal, kira-kira enam kilometer panjangnya. Tanah kering berdebu, rerumputan menari ditiup angin, dan suara tawa mereka bersahut-sahutan seperti musik dari masa muda yang riang.
Dalam perjalanan pulang, langit mulai menggelap, waktu menuntut mereka kembali ke asrama. Tiwi, dengan suara selembut bisikan angin di telinga, berkata pada Tingang,
“Aku lelah. Tadi siang cuma jajan sedikit di sekolah.”
Tingang, dengan senyum jahil khas remaja, menjawab,
“Saya gendong saja, ya?”
Tiwi tertawa kecil, seperti gemericik air di antara bebatuan.
“Benarkah mau gendong? Badan saya cukup besar, loh. Yakin mampu?”
Senyum manisnya menyelinap ke dalam dada Tingang, membuat jantungnya berdetak tak beraturan. Ia kehilangan arah langkah, tersandung kerikil kecil. Jalanan kering tak bersuara, namun hatinya gaduh tak karuan.
Beberapa menit berlalu, Tiwi benar-benar terlihat letih. Langkahnya melambat, nafasnya pendek-pendek.
“Sudah, saya gendong ya,” kata Tingang, kali ini lebih sungguh.
Tanpa banyak kata, Tiwi melingkarkan kedua tangannya dari belakang. Dalam sekejap, Tingang memikulnya di punggung, tubuhnya berat namun hatinya ringan. Dunia seperti berhenti sebentar, membiarkan mereka menikmati momen kecil yang diam-diam begitu besar. Mungkin ini cinta monyet—ya, cinta yang datang seperti hujan bulan Juni, singkat, manis, dan tak mudah dilupakan.
Momen itu, walau hanya sejenak, tertanam dalam seperti akar yang menjulur ke dasar tanah kenangan. Kadang, tanpa diduga, kenangan itu muncul kembali, membelokkan langkah hati ke masa lalu.
Selama SMP, Tiwi tinggal di asrama. Pertemuan hanya mungkin di jam pulang sekolah. Tak jarang ia berdalih hendak bertemu keluarga dari kampung, padahal hanya ingin menatap wajah yang mulai bersemayam diam-diam di sudut hatinya.
Ujian datang seperti badai yang tak bisa ditunda. Malam-malam mereka berubah menjadi arang hitam, panjang, dan membakar energi. Belajar dengan sistem kebut semalam menjadi ritual wajib. Mereka mengadu nasib pada buku, mengandalkan sisa-sisa tenaga dan kopi murah dari warung depan sekolah. Kegagalan bukan pilihan, karena harus mengulang satu tahun terasa seperti dihukum waktu.
Tingang tinggal di rumah kos kecil berukuran 4 x 6 meter, berdinding papan yang kadang berderit jika ditiup angin. Setelah satu tahun, rumah itu berhasil dibeli oleh kedua orang tuanya sebuah pencapaian besar meski listrik masih menumpang dari tetangga. Satu bola lampu kuning menerangi malam-malamnya yang sunyi.
Menu makan sehari-harinya sederhana: kangkung, tahu, tempe, dan mi instan. Kangkung menjadi raja di antara sayur-mayur lain—mudah didapat, murah, dan selalu setia di pasar. Kadang, di antara bunyi panci dan desir api, ia merenung: bagaimana rasa lapar bisa menjadi guru kehidupan?
Akhirnya, perjalanan itu menutup satu bab: Tingang menyelesaikan sekolah menengah pertamanya.
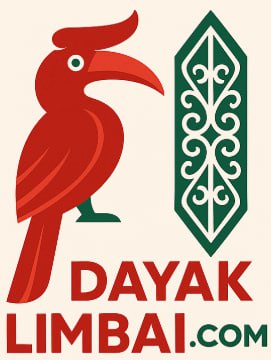











Komentar